Merangkai Hikmah dari Tanah Suci
Dulu, waktu SMA, guru matematika favorit saya pernah berkata.
"Manusia itu ada empat tipe. Tipe pertama yang paling beruntung, yakni mereka yang tahu kalau mereka tahu. Tipe kedua, mereka ga tahu kalau mereka tahu. Tipe ketiga, mereka yang tahu kalau mereka ga tahu. Dan yang keempat, yang paling celaka, yaitu mereka yang ga tahu kalau mereka ga tahu."
Nasihat ini menancap dalam hati saya, terbersit pemikiran bahwa kalau mau memperbaiki diri berarti kita harus sadar dulu kalau ada yang harus diperbaiki, kita harus menerima dulu kalau ada yang masih salah dan tidak sesuai.
Saya ingin sedikit bercerita tentang salah satu pengalaman pembuka mata yang cukup berat untuk diakui. Kilas balik, saat berhaji kemarin, saya terkagum dan takjub atas tumpahan manusia yang luar biasa meninggalkan aneka urusan dunianya semata untuk menjawab panggilan Rabb-Nya, tapi disaat yang sama pula saya ditampar untuk sadar bahwa nyatanya pe-er saya (dan kita) masih banyak. Dan bagi saya haji ini miniatur umat, dimana muslim dari aneka negara tumpah ruah disana.
Di saat berhaji ini masanya saya menemukan orang-orang berhati malaikat yang barang bawaannya ke tenda bukanlah didominasi keperluannya, tapi semata aneka obat dan hadiah yang akan dibagi-bagikan pada saudara lainnya.
Di masa ini, masanya saya menemukan orang-orang yang akan mengurusi jemaah lain yang sakit, sekalipun ia pada dasarnya adalah jemaah biasa yang berlatar dokter, sampai-sampai mengesampingkan kesehatan dirinya sendiri.
Di masa ini pula, masanya saya menemukan orang-orang bersosok pemimpin yang rela makan terakhir demi tuntas memastikan seluruh orang dalam tenda sudah kebagian makanan.
Di masa ini pula, masanya saya pertama kali menyaksikan kedermawanan yang luar biasa, kerumunan orang mengantri panjang untuk mengambil makan siang yang disediakan cuma-cuma oleh entah siapa.
Rasanya hati saya buncah oleh harap, buncah oleh syukur menyaksikan contoh langsung sikap itsar; mendahulukan orang lain yang selama ini sering kali tergambar dalam sejarah di masa lalu.
Tapi, di masa ini pula, saya menemukan mereka yang berupaya mengelabui uang kembalian, sampai didesak barulah diberikan seutuhnya, tak jauh dari masjidil haram.
Di masa ini pula saya melihat perilaku menyelak seolah jadi budaya biasa. Entah disengaja atau khilaf terbawa arus jadi ikut-ikutan.
Di masa ini pula saya melihat para supir taksi bisa seenaknya melambungkan harga sampai sepuluh kali lipat harga biasa tapi penumpang tetap membayar karena tak ada pilihan, sekalipun dengan wajah masam dan tak rela hati.
Di masa ini pula saya menyaksikan detik sebelumnya mengulang hafalan, di detik selanjutnya mengelabui penumpang.
Belum kesemrawutan, ketidakjelasan aturan, dan pemenang adalah yang paling keras bentakan suaranya.
Saya sedih, bukan karena merasa lebih tinggi, bagaimana mau merasa lebih tinggi kalau kita sejatinya satu tubuh? Saya sedih karena melihat umat yang saya turut serta disana, masih kerap terlupa.
Saat kembali menginjakan kaki ke kawasan Eropa, saat itu transit di Heathrow UK, rasanya kembali ke keteraturan. Kembali ke mengantri jauh dari batas pemeriksaan, saat kanan kiri dibiarkan longgar tanpa takut akan ada yang menerabas antrian. Kembali ke pemandangan membuang sampah pada tempat yang disediakan. Dan sejenisnya.
Padahal sejatinya setiap ibadah mengajarkan pengendalian diri, mengajarkan taat pada aturan. Seharusnya mereka yang belajar pada kita tentang keteraturan. Seharusnya. Nyatanya saat ini saya harus mengakui bahwa pada beberapa aspek kita masih tertinggal. Bukan, bukan lantas mengelukan dan menjadikan Barat sebagai kiblat pemikiran. Tapi justru sebagai refleksi diri, bahwa nyatanya ada beberapa aspek yang perlu kita perbaiki dengan kembali menerapkan ajaran yang kita sudah miliki teorinya.
Mungkin beginilah potret zaman keempat, dimana kita masih banyak yang tertidur dari syariat, iya, termasuk saya sendiri.
Salah satu buah manis dari berhaji kemarin adalah semangat untuk terus mempelajari diin ini karena nyatanya saya jadi tahu ada begitu banyak yang saya belum kuasai, ada banyak yang harus diperbaiki. Terutama untuk diri saya sendiri.
Lalu apakah saya mau untuk kembali ke tanah suci bahkan berhaji lagi bila Allah beri kesempatan? Tentu! Walau ada sedih disana-sini, tapi lagi-lagi, saya melihatnya sebagai ujian di masa ini, saat kita harus menyadari dan memaklumi bahwa diri-diri kita masih belajar untuk menjadi kaffah, sekalipun yang bermukim di tanah suci, sekalipun yang berada di tanah suci.
"Nasehat itu permata. Baik diselipkan ke saku, digenggamkan ke tangan, ataupun ditimpukkan ke muka, ia tetaplah permata. Ambil permatanya. Sebab ia jauh lebih mudah daripada mencarinya sendiri ke kedalaman bumi." -Salim A. Fillah
"Manusia itu ada empat tipe. Tipe pertama yang paling beruntung, yakni mereka yang tahu kalau mereka tahu. Tipe kedua, mereka ga tahu kalau mereka tahu. Tipe ketiga, mereka yang tahu kalau mereka ga tahu. Dan yang keempat, yang paling celaka, yaitu mereka yang ga tahu kalau mereka ga tahu."
Nasihat ini menancap dalam hati saya, terbersit pemikiran bahwa kalau mau memperbaiki diri berarti kita harus sadar dulu kalau ada yang harus diperbaiki, kita harus menerima dulu kalau ada yang masih salah dan tidak sesuai.
Saya ingin sedikit bercerita tentang salah satu pengalaman pembuka mata yang cukup berat untuk diakui. Kilas balik, saat berhaji kemarin, saya terkagum dan takjub atas tumpahan manusia yang luar biasa meninggalkan aneka urusan dunianya semata untuk menjawab panggilan Rabb-Nya, tapi disaat yang sama pula saya ditampar untuk sadar bahwa nyatanya pe-er saya (dan kita) masih banyak. Dan bagi saya haji ini miniatur umat, dimana muslim dari aneka negara tumpah ruah disana.
Di saat berhaji ini masanya saya menemukan orang-orang berhati malaikat yang barang bawaannya ke tenda bukanlah didominasi keperluannya, tapi semata aneka obat dan hadiah yang akan dibagi-bagikan pada saudara lainnya.
Di masa ini, masanya saya menemukan orang-orang yang akan mengurusi jemaah lain yang sakit, sekalipun ia pada dasarnya adalah jemaah biasa yang berlatar dokter, sampai-sampai mengesampingkan kesehatan dirinya sendiri.
Di masa ini pula, masanya saya menemukan orang-orang bersosok pemimpin yang rela makan terakhir demi tuntas memastikan seluruh orang dalam tenda sudah kebagian makanan.
Di masa ini pula, masanya saya pertama kali menyaksikan kedermawanan yang luar biasa, kerumunan orang mengantri panjang untuk mengambil makan siang yang disediakan cuma-cuma oleh entah siapa.
Rasanya hati saya buncah oleh harap, buncah oleh syukur menyaksikan contoh langsung sikap itsar; mendahulukan orang lain yang selama ini sering kali tergambar dalam sejarah di masa lalu.
Tapi, di masa ini pula, saya menemukan mereka yang berupaya mengelabui uang kembalian, sampai didesak barulah diberikan seutuhnya, tak jauh dari masjidil haram.
Di masa ini pula saya melihat perilaku menyelak seolah jadi budaya biasa. Entah disengaja atau khilaf terbawa arus jadi ikut-ikutan.
Di masa ini pula saya melihat para supir taksi bisa seenaknya melambungkan harga sampai sepuluh kali lipat harga biasa tapi penumpang tetap membayar karena tak ada pilihan, sekalipun dengan wajah masam dan tak rela hati.
Di masa ini pula saya menyaksikan detik sebelumnya mengulang hafalan, di detik selanjutnya mengelabui penumpang.
Belum kesemrawutan, ketidakjelasan aturan, dan pemenang adalah yang paling keras bentakan suaranya.
Saya sedih, bukan karena merasa lebih tinggi, bagaimana mau merasa lebih tinggi kalau kita sejatinya satu tubuh? Saya sedih karena melihat umat yang saya turut serta disana, masih kerap terlupa.
Saat kembali menginjakan kaki ke kawasan Eropa, saat itu transit di Heathrow UK, rasanya kembali ke keteraturan. Kembali ke mengantri jauh dari batas pemeriksaan, saat kanan kiri dibiarkan longgar tanpa takut akan ada yang menerabas antrian. Kembali ke pemandangan membuang sampah pada tempat yang disediakan. Dan sejenisnya.
Padahal sejatinya setiap ibadah mengajarkan pengendalian diri, mengajarkan taat pada aturan. Seharusnya mereka yang belajar pada kita tentang keteraturan. Seharusnya. Nyatanya saat ini saya harus mengakui bahwa pada beberapa aspek kita masih tertinggal. Bukan, bukan lantas mengelukan dan menjadikan Barat sebagai kiblat pemikiran. Tapi justru sebagai refleksi diri, bahwa nyatanya ada beberapa aspek yang perlu kita perbaiki dengan kembali menerapkan ajaran yang kita sudah miliki teorinya.
Mungkin beginilah potret zaman keempat, dimana kita masih banyak yang tertidur dari syariat, iya, termasuk saya sendiri.
Salah satu buah manis dari berhaji kemarin adalah semangat untuk terus mempelajari diin ini karena nyatanya saya jadi tahu ada begitu banyak yang saya belum kuasai, ada banyak yang harus diperbaiki. Terutama untuk diri saya sendiri.
Lalu apakah saya mau untuk kembali ke tanah suci bahkan berhaji lagi bila Allah beri kesempatan? Tentu! Walau ada sedih disana-sini, tapi lagi-lagi, saya melihatnya sebagai ujian di masa ini, saat kita harus menyadari dan memaklumi bahwa diri-diri kita masih belajar untuk menjadi kaffah, sekalipun yang bermukim di tanah suci, sekalipun yang berada di tanah suci.
"Nasehat itu permata. Baik diselipkan ke saku, digenggamkan ke tangan, ataupun ditimpukkan ke muka, ia tetaplah permata. Ambil permatanya. Sebab ia jauh lebih mudah daripada mencarinya sendiri ke kedalaman bumi." -Salim A. Fillah
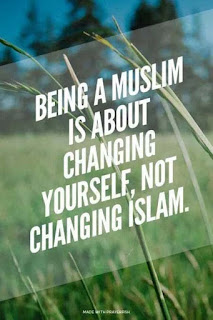



Comments
Post a Comment